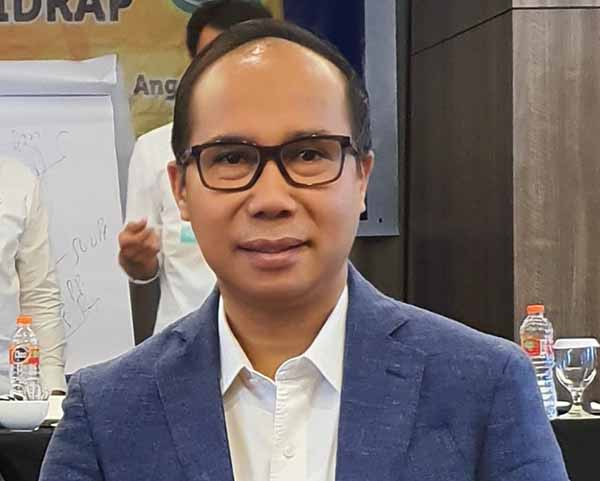Oleh: Muhadam Labolo
Survei _Digital Civility Index_ (DCI,2020) menunjukkan bahwa tingkat kesopanan _warganet_ di Indonesia paling buruk di Asia Tenggara. Penyebabnya tiga hal, _hoax_ dan penipuan yang mencapai 47%, ujaran kebencian di angka 27%, dan diskriminasi sebesar 13%. Mirisnya, 68% pegiat digital di ruang publik didominasi oleh kelompok dewasa. Kontribusi mereka mempengaruhi komunikasi kolektif yang saling menegasikan.
Ruang publik digital dipenuhi toksin. Ekses teknologi menciptakan luapan informasi berlebih. Meluber kemana-mana, seperti lahar panas yang menghantam kesantunan sosial. _Public sphere_ digital tak menyediakan waktu bagi _warganet_ untuk berpikir. Setiap cuitan pendek melahirkan respon hingga _emotion_ kontra produktif. Saling menyambar bahkan menguliti perasaan. Sebagian tampil ekspresif, unjuk diri, kendati dangkal makna. Sisanya diam dan menarik diri. Ruang publik telah berubah menjadi ancaman serius bagi kredibilitas seorang pakar sekaliber apapun. Mereka bisa dihina dan dinistakan.
Kita hidup dalam ruang publik digital tanpa batas. Setiap _warganet_ bersembunyi dibalik topeng akun masing-masing. Raganya raib, namun perasaan dan pikirannya muncul laksana iklan pendek yang menipu. Ruang publik digital seakan melenyapkan jati diri. Pesona kemuliaan diri sirna, kecuali gambar wajah yang berganti saban hari. Peran pun dapat disesuaikan, namun sulit bagi awam membedakan mana kritikus dan mana penghina. Apalagi jika pemantik ruang publik menyuguhi _headline_ provokatif. Tanpa disulut, api membakar sekam. Ruang publik segera dijejali bara kesumat oleh _haters_ yang datang dari segala penjuru.
Ditengah tumpahan informasi yang berlimpah itu, daya kritis kita seakan krisis. Menyerah pada _running text._ Nalar kita putus sebelum sempat menelisik lewat epistem alternatif. Tak ada waktu mendalami pengetahuan lewat buku, yang tersedia hanya sumber instan, _wikipedia_ dalam _goegle._ Dalam kependekan nalar akibat rendahnya gelombang tangkap itu, yang tumbuh subur hanya potensi titik pisah, bukan titik temu. Titik pisah melahirkan pertengkaran, kebencian dan permusuhan berbau identitas rasial dan religi. Inilah toksin yang mewabah di ruang publik, menjangkiti _netizen,_ menciptakan epidemi baru yang membutuhkan semacam vaksin digital agar tak melahirkan _zombie._
Baca juga: Pelemahan Demokrasi dan Rekonstruksi Parpol
Bila dikemas dengan baik, ruang publik digital idealnya mampu menumbuhkan titik temu bagi perdamaian abadi, kohesi sosial, dan persatuan dalam keragaman. Tanpa komitmen itu, ruang publik digital hanya memproduk racun bagi keretakan soliditas bernegara. Setiap _warganet_ seakan tak berikatan dengan asosiasi apapun termasuk negara. Mereka hidup otonom dengan jalan pikir dan perasaan masing-masing, sekalipun di alam nyata tak seorangpun dapat melepaskan diri dari tanggungjawab sebagai warga negara.
Ruang publik digital seharusnya tak dibiarkan seperti pasar bebas sebagaimana ide Smith (1776). Ruang itu perlu dikemas agar tumbuh sesuai gagasan Habermas (2010), yaitu sarana komunikasi, ruang perjumpaan ide, serta dialektika demokrasi. Tanpa kontrol, bukan mustahil ruang publik digital dengan mudah didikte oleh para pendengung _(buzzer),_ oligarkhi, dan kesewenangan negara. Para penjelas ilmu bahkan gentar mengeluarkan opini karena trauma di _bully._ Dibongkar masa lalu, diintip perilaku dan dipermainkan seperti sekawanan semut merah mengurai seekor lebah tak berdaya.
Ada baiknya ruang publik digital ditata kembali agar keadaban sosial tak punah sebagai ciri manusia sejati. Kecanggihan teknologi informasi semestinya membantu manusia mencapai tujuan dengan mudah. Bukan sebaliknya, mekarnya kebiadaban sosial yang merusak sendi-sendi kemanusiaan. Tak salah jika tujuan negara menurut Roger Soltau (1951) adalah menjamin berkembangnya daya cipta warga negara sebebas-bebasnya, termasuk diruang publik digital. Namun di saat yang sama mesti dilandasi oleh tujuan lain kata Thomas Aquinas (1969), yaitu tercapainya hidup tersusila dan kemuliaan hakiki menurut spirit keagamaan. Maknanya, negara mesti hadir untuk menjernihkan kualitas ruang publik digital yang tercemar toksin akibat polusi dialektika tuna etika. *
(Penulis Adalah Dekan Fakultas Politik Pemerintahan IPDN)