Sekarang, bandingkan dengan gaji pokok kepala daerah yang hanya berkisar 2,7-3,5 jt ditambah tunjangan sekitar 40 jutaan. Fakta ini semakin meyakinkan mengapa peran _cukong_ sangat dibutuhkan. Lalu dimana sumber masalahnya?
Dalam perspektif pemerintahan _(kybernologi,_ Ndraha, 2002), pengelolaan subkultur kekuasaan tampak jauh dari tiga prinsip utama, yaitu _berkuasa semudah mungkin, menjalankan seefektif mungkin,_ dan _mempertanggungjawabkan seformal mungkin._ Praktek pemilukada kita memperlihatkan bahwa pola sirkulasi kekuasaan dari satu rezim ke rezim selanjutnya tidaklah mudah dan teramat mahal.
Jalan panjang yang mesti dilewati oleh setiap paslon secara logika memungkinkan mereka menghimpun modal demi mencapai puncak kekuasaan. Itu bukan sepenuhnya salah mereka, tapi lebih karena pilihan mekanisme dalam sistem pemilukada yang tak rasional. Mekanisme semacam itu membutuhkan jumlah bukan isi. Akibatnya, banyak paslon terpilih karena jumlah kepala, bukan isi kepala.
Diakui bahwa jumlah kepala penting sebagai dasar legitimasi, tetapi isi kepala pun tak kalah pentingnya sebagai kompas yang akan membawa daerah menuju kesejahteraan masyarakat. Realitas ini mengingatkan kita pada ajaran filosof Socrates (399 M), jangan paksakan demokrasi langsung pada masyarakat dengan tingkat pendidikan dan pendapatan rendah, sebab yang akan terpilih bukan mereka yang kompeten, tetapi mereka yang lebih populer dan bermodal besar.
Berkali-kali dalam berbagai kesempatan ceramah dihadapan DPRD se-Indonesia, saya mengatakan bahwa menihilkan _money politics_ dalam pesta pemilukada adalah hal mustahil, baik lewat mekanisme langsung maupun tak langsung. Bila dideteksi, laju perjalanan uang panas itu mengalir deras pada dua segmen utama, yaitu sekelompok elit parpol dalam bentuk gelondongan, atau membanjir ke khalayak ramai yang didatangi bak penerima bantuan di panti asuhan.
Artinya, mau langsung atau tidak, tetap saja penyakit kronis _money politics_ itu hampir mendarah-daging bagi masyarakat tuna _integrity._ Pertanyaan yang lebih realistis dalam konteks ini adalah mekanisme manakah yang lebih mudah dikontrol, efisien, efektif, rendah kerumunan, kebal epidemi, serta tak mudah menodai integritas moral masyarakat? Bahwa ia tetap berpotensi dihadiri _cukong_ tentu tak dapat dihindari, sebab kita sedang memilih pemimpin dibumi, bukan malaikat di surga.
Mesti pula diakui bahwa dalam peristiwa pemilukada yang terlibat bukan saja _cukong,_ juga birokrat opurtunis dan politisi kelas lokal. Jadi, yang dapat kita lakukan hanyalah meminimalisasi sampai titik terendah, yaitu mengubah mekanisme sistem pemilukada, seraya meningkatkan sistem meningkatkan pengawasan sekelompok kecil orang. Bukankah jauh lebih efektif bila PPATK mengontrol transaksi pada 45 orang wakil rakyat daripada memburu serangan fajar pada 450 ribu pemilih irrasional dan lapar?
Dengan sendirinya kita tak membutuhkan tahapan panjang yang memeras kocek paslon lewat _cukong,_ menghindari kerumunan sosial, mengurangi resiko keterlibatan penyelenggara pemilukada mulai KPUD, Bawaslu dan organisasi TPS ditingkat terbawah. Bahkan menghindari kepala daerah sebaik apapun terjerumus dalam politik _balas budi_ dan _balas dendam_ yang membawa mereka di buih oleh KPK.
Semua perubahan mekanisme itu sekaligus menjadi sistem anti pandemi, menurunkan _political cost_ paslon, mengurangi potensi konflik, mengefisienkan APBD, serta menihilkan berbagai keperluan yang tak perlu dan menguatirkan, termasuk menjauhkan moral masyarakat dari infeksi korupsi. *
Baca juga: Masa Depan Politik Demokrasi
(penulis adalah Dekan Fakultas Politik Pemerintahan IPDN)


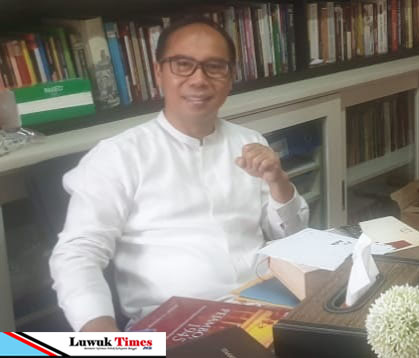
















Discussion about this post