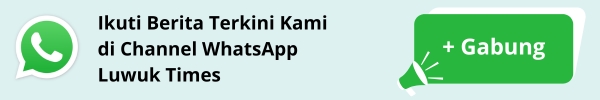Oleh: Supriadi Lawani
MINGGU lalu saya mendampingi seorang anak muda di Polres Banggai. Ia diperiksa atas laporan sebuah perusahaan nikel yang beroperasi di kampungnya.
Usianya sebaya dengan anak saya, meski ia memanggil saya “kakak”.
Panggilan itu membuat saya merasa muda—atau lebih tepatnya, merasa sedang berhadapan dengan generasi yang lahir dari kesadarannya sendiri.
Anak muda ini kehilangan ayahnya, bukan karena mati tapi pergi karena perempuan lain.
Ibunya sedang sakit berat. Hidupnya tidak mudah.
Tetapi ia berbicara dengan kosa kata yang jernih, berpikir logis, kritis, dan berani melawan ketidakadilan—dengan cara khas anak muda.
Saya dan istri saya kagum. Bukan karena keberaniannya semata, tapi karena kejernihan kesadarannya.
Pertemuan itu membawa pikiran saya kembali pada Pramoedya Ananta Toer, khususnya Jejak Langkah dalam Tetralogi Buru.
Dalam Jejak Langkah, Pramoedya tidak sedang menulis kisah cinta dua anak muda terpelajar.
Ia sedang menunjukkan bagaimana kebudayaan melahirkan kesadaran politik.
Minke, pemuda Jawa. An San Mei, gadis Tionghoa.
Darah berbeda, asal-usul berbeda, tetapi keduanya dibentuk oleh kebudayaan yang sama: pendidikan model Eropa, modernitas, dan zaman baru.
Mereka membaca buku yang sama, belajar cara berpikir yang sama, dan—tanpa sadar—mulai mengajukan pertanyaan yang sama: untuk apa hidup, jika bukan untuk bebas?
Ketika Minke mengatakan bahwa mereka keluar dari “satu pabrik yang sama bernama zaman baru”, Pram sedang menyindir kolonialisme.
Penjajahan ingin mencetak manusia patuh: terdidik tetapi tunduk.
Namun yang lahir justru sebaliknya—manusia yang sadar, gelisah, dan tak mau lagi diperintah.
Di titik itu, pagar ras runtuh. Jawa dan Tionghoa tak lagi berhadap-hadapan.
Yang ada hanyalah dua manusia modern yang sama-sama merasa terjajah.
Kesadaran ini bukan hasil propaganda, melainkan hasil kebudayaan.
Buku, sekolah, bahasa, dan pergaulan modern membentuk cara berpikir baru: bahwa manusia dilahirkan setara, dan tidak satu pun bangsa pantas diperintah bangsa lain.
Inilah roh yang sama dengan semboyan Revolusi Prancis: Liberté, Égalité, Fraternité—kebebasan, persamaan, dan persaudaraan.
Bukan sebagai slogan Eropa, melainkan sebagai kebutuhan universal manusia.
Pram ingin mengatakan: Indonesia tidak lahir dari kesamaan darah, melainkan dari kesamaan kesadaran.
Kesadaran yang dibentuk oleh kebudayaan, diperkeras oleh penindasan, dan diarahkan pada satu tujuan: kemerdekaan.
Dialog Minke dan An San Mei dalam novel legendaris itu sesungguhnya bisa saja terjadi pada anak muda Indonesia hari ini.
Hari ini pun adalah zaman baru—zaman teknologi informasi yang menghubungkan dunia, zaman sains yang kian maju, zaman pengetahuan yang seharusnya membebaskan.
Namun ironisnya, Indonesia justru seperti hendak melangkah mundur.
Demokrasi yang dulu diperjuangkan anak muda 1998 terasa makin tergerus.
Kebebasan berekspresi dipersempit. Pidana, represi, dan teror dipertontonkan hampir setiap hari.
Di tengah kegelisahan itu, pertanyaan Minke tetap relevan: untuk apa hidup, jika bukan untuk bebas?
Saya percaya, sebagaimana pada zaman Minke dan An San Mei, akan selalu lahir anak-anak muda dengan imajinasi baru—yang menolak tunduk, menolak takut, dan berani membayangkan zaman baru bagi Indonesia.
Zaman di mana kebudayaan kembali melahirkan kesadaran, dan kesadaran mendorong bangsa ini bergerak ke arah yang lebih adil, lebih bebas, dan lebih manusiawi.
Minke dan An San Mei adalah bayangan awal bangsa yang belum ada. Dan mungkin, hingga hari ini, masih terus diperjuangkan. *