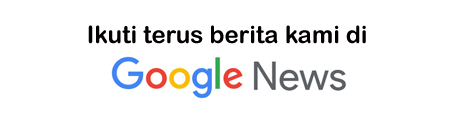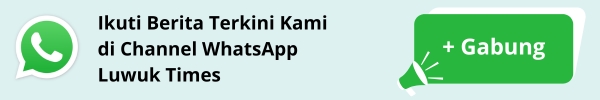Oleh: Herdiyanto Yusuf
SAYA masih mengelola Tabloid Bingkai ketika kali pertama istilah Jurnalisme Sastrawi dipopulerkan oleh Andreas R. Harsono pada tahun 2000-an.
Tabloid lokal terbitan Gorontalo yang berumur pendek ini saya kelola bersama Elnino M. Husein Mohi, wartawan “compang-camping” yang akhirnya banting setir menjadi politikus handal.
Itu setelah—sambil tetap menjadi wartawan—ia menyelesaikan S2 di jurusan komunikasi politik Universitas Indonesia dengan beasiswa Fulbright.
Saat ini Elnino menjadi anggota DPR RI dari Partai Gerindra untuk periode kedua, setelah dua periode sebelumnya menjadi anggota DPD-RI.
Oh ya, soal julukan wartawan compang-camping itu lebih karena gaya berpakaiannya yang selalu lusuh tapi nyentrik.
Soal otak? Jangan tanya. Ia salah satu wartawan panutan saya, paling hebat kala itu. (Sekali waktu saya perlu menulis panjang tentang ini).
Sebagai wartawan muda yang masih sangat idealis tapi jauh dari sumber literasi, keinginan menaikkan kapasitas jurnalistik terpaksa dipenuhi dengan cara gratis.
Salah satunya dengan berlangganan Majalah Pantau, terbitan Utan Kayu yang didirikan antara lain oleh Andreas R. Harsono—wartawan senior sekaligus pelopor Jurnalisme Sastrawi di Indonesia.
Majalah itu saya dapatkan gratis lewat kebaikan kawan-kawan AJI.
Di majalah yang sebagian masih saya simpan hingga kini, penulis-penulis hebat silih berganti unjuk kemampuan menulis laporan naratif panjang—laiknya berita fakta dengan gaya bercerita ala novel Fredy S.
Beberapa nama populer saat itu: Nezar Patria, Dandhy Dwi Laksono, dan satu lagi dari Sulawesi Utara, Ahmad Taufik Pontoh.
Saya teringat lagi jurnalisme sastrawi ini ketika ada kawan mengirim pesan WhatsApp, menanyakan kenapa saya belakangan gemar menulis cerpen.
Saya menjawab pendek: “Untuk terus melatih imajinasi dan kemampuan menulis naratif deskriptif.
Kemampuan menghidupkan detail sensorik sebuah peristiwa empirik—entah fakta atau fiksi.”
Inilah inti jurnalisme sastrawi. Genre jurnalisme yang sejatinya sudah berkembang sejak era New Journalism di Amerika Serikat tahun 1960-an, dipelopori oleh Truman Capote dan Tom Wolfe.
Di Indonesia, gaya ini mulai dikenal satu dasawarsa kemudian lewat majalah Tempo ala Goenawan Mohamad.
Yang paling saya ingat dari pelajaran itu adalah istilah: Show, Don’t Tell—tunjukkan, jangan sekadar ceritakan.
Prinsip ini berasal dari dunia sastra, tapi banyak diadopsi jurnalis agar laporan mereka hidup dan imersif.
Karena itu, menulis cerpen sejatinya seperti kembali belajar teknik jurnalisme sastrawi.
Dan di titik ini saya makin yakin: karya fiksi, termasuk cerpen, bukanlah pelarian dari dunia nyata.