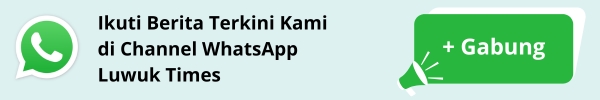Oleh: Supriadi Lawani
PANJI menggelar stand up comedy di panggung besar. Ditayangkan di Netflix. Viral. Itu saja sebenarnya sudah cukup menjelaskan bahwa yang terjadi adalah kerja seni—komedi, satire, kritik sosial. Tidak lebih, tidak kurang.
Bahwa kemudian sebagian pendukung Gibran merasa tersinggung, marah, atau panas telinga, itu wajar. Dalam demokrasi, perasaan tersinggung bukan barang haram. Setiap kritik selalu melahirkan resistensi. Itu normal.
Yang tidak normal—bahkan ngeri—adalah reaksi setelahnya.
Tiba-tiba muncul laporan polisi. Tiba-tiba ada demo. Tiba-tiba ada sekelompok orang yang mengatasnamakan “pemuda NU” dan “pemuda Muhammadiyah” turun ke jalan, membawa moral, membawa identitas keagamaan, dan membawa tuntutan hukum terhadap seorang komedian.
Entah benar atau tidak mereka representasi resmi organisasi itu saya tidak tahu. Tapi faktanya, media dan media sosial merekamnya, menyebarkannya, dan menjadikannya konsumsi publik.
Di titik inilah rasa ngeri itu muncul.
Bukan karena Panji lucu atau tidak lucu. Bukan karena kritiknya tepat atau meleset. Tapi karena kita menyaksikan sesuatu yang jauh lebih mengkhawatirkan: ada sekelompok orang yang takut pada komedi.
Takut pada lelucon. Takut pada satire. Takut pada tawa.
Stand up comedy dibalas dengan laporan polisi. Punchline dibalas dengan pasal. Materi komedi dibalas dengan buzzer.
Ini bukan sekadar soal Panji. Ini soal watak kekuasaan dan para pendukungnya. Kekuasaan yang percaya diri tidak akan alergi pada komedi. Ia akan ditertawakan, lalu—kalau perlu—menertawakan balik.
Kalau ada yang merasa Panji keliru, jawabannya sederhana:
Naik ke panggung. Bikin stand up tandingan. Lawan dengan humor. Lawan dengan kecerdasan.
Bukan dengan kriminalisasi.
Karena ketika komedi dibalas dengan ancaman hukum, sesungguhnya yang sedang dipertontonkan bukan kewibawaan, melainkan ketakutan.
Ketakutan bahwa tawa lebih berbahaya daripada kritik akademik. Ketakutan bahwa satu mic dan satu panggung bisa lebih mengganggu daripada ribuan spanduk.
Dan lebih mengerikan lagi: ketakutan itu dibungkus dengan identitas agama dan pemuda. Seolah-olah iman perlu dibela dari lelucon. Seolah-olah organisasi keagamaan rapuh oleh satire seorang komedian.
Padahal agama yang matang tidak takut ditertawakan. Demokrasi yang sehat tidak panik oleh komedi. Negara yang dewasa tidak mengirim polisi untuk mengejar punchline.
Kalau hari ini kita membiarkan komedian dilaporkan karena lelucon, maka kita seperti mengulang sejarah yang sama negara yang takut pada puisi,dan Wiji Thukul hilang sampai sekarang dan hari ini komedi, besok mungkin giliran puisi akan di laporkan, lusa giliran lagu. Minggu depan giliran status medsos.
Dan saat itu, kita mungkin baru sadar: yang ngeri bukan komedinya—tapi mereka yang kehilangan selera humornya. Dan ini Ngeriii…!!! *